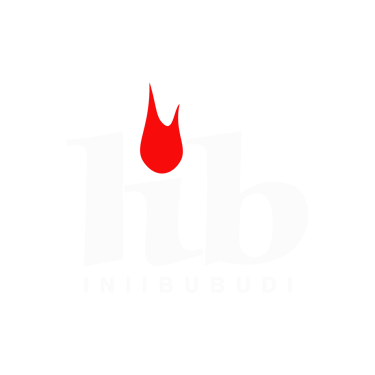Buku, Anak Muda dan Ketakutan Negara
ESAI
Oleh: Djoko Subinarto
11/1/2025


KETIKA negara takut pada buku, itu artinya negara takut pada keberanian warga untuk berpikir berbeda.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya menilai langkah kepolisian yang menyita buku untuk menjerat sejumlah orang dalam kasus kerusuhan di Jawa Timur pada tanggal 29–30 Agustus 2025 sebagai tindakan yang berpotensi membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi.
Koordinator KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, seperti dikutip sejumlah media, menyebut penyitaan buku tidak hanya mengkriminalisasi wacana kritis, tetapi juga menunjukkan adanya ketakutan negara terhadap anak muda yang gemar membaca serta memiliki pandangan kritis.
Pertanyaannya adalah: mengapa justru anak muda yang gemar membaca dan berpikir kritis dianggap sebagai ancaman? Bukankah mereka ini aset bagi masa depan bangsa dan negara kita?
Mengelola Perbedaan Pandangan
Kecurigaan terhadap kaum muda yang membaca buku tak jarang lahir dari kecemasan politik. Pemegang kekuasaan khawatir akan muncul generasi yang kritis dan sulit dikendalikan. Padahal, sikap kritis adalah bagian sah dari demokrasi yang sehat. Ketakutan itu justru menyingkap ketidakmampuan negara dalam mengelola perbedaan pandangan.
Michel Foucault pernah menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk kekuasaan. Artinya, siapa yang menguasai pengetahuan, memiliki potensi untuk menantang struktur dominasi. Dari perspektif ini, wajar jika negara merasa waswas terhadap anak muda yang haus pengetahuan. Namun, jika rasa takut itu berlebihan, maka yang muncul bukan demokrasi, melainkan represi.
Membaca membuat orang bertanya, mengkritisi, dan meragukan kebenaran tunggal. Justru inilah fungsi utama literasi dalam masyarakat demokratis. Tanpa kemampuan kritis, demokrasi hanya akan jadi ritual prosedural tanpa substansi.
Ironisnya, di saat negara perlu mendorong program peningkatan literasi, negara juga menaruh kecurigaan pada bacaan tertentu. Ada kontradiksi yang sulit disembunyikan di sini. Di satu sisi, negara menginginkan warga yang melek huruf dan berpengetahuan. Namun, di sisi lain, ia juga takut pada warga yang melek wacana dan pengetahuan. Kontradiksi ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan visi pembangunan manusia di negeri ini.
Dengan membaca buku, kita bisa menemukan perspektif baru tentang sejarah, keadilan, atau masa depan. Proses ini tidak selalu mulus, kadang melahirkan kegelisahan. Namun, kegelisahan intelektual yang lahir sebagai hasil membaca buku justru tanda bahwa literasi bekerja.
Ketidakpercayaan dan kecurigaan negara pada anak muda yang membaca buku dapat berakibat serius. Ia bisa melahirkan generasi yang memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena takut. Demokrasi kehilangan daya hidup ketika kritik dibungkam sejak di level bacaan. Pada akhirnya, negara sendiri yang rugi, karena kehilangan mitra kritis untuk turut memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti sama-sama ketahui, aktivitas membaca selalu membuka ruang perbedaan. Setiap orang bisa menafsirkan teks dengan cara yang berbeda-beda, dan itu sah. Perbedaan tafsir inilah yang melatih toleransi dan pluralitas. Jika perbedaan saja ditakuti, berarti negara belum siap menerima realitas demokrasi.
Anak muda yang rajin membaca buku umumnya lebih peka terhadap isu-isu keadilan sosial. Mereka tidak puas dengan jawaban dangkal, melainkan mencari penjelasan yang lebih mendalam. Sensitivitas inilah yang kadang membuat penguasa gelisah.
Persoalan tersebut sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara lain. Kita bisa melihat bagaimana rezim di berbagai belahan dunia membatasi akses bacaan tertentu. Ketakutan mereka sama bawa anak muda yang membaca bisa berubah menjadi anak muda yang menuntut perubahan. Di sinilah literasi menjadi medan politik, bukan cuma aktivitas intelektual semata.
Yang mungkin luput dipahami selama ini adalah bahwa membaca buku tidak otomatis membuat orang radikal. Membaca buku justru sering menjadi jalan untuk memahami kompleksitas dunia. Anak muda yang kritis setelah membaca buku tidak identik dengan pemberontakan yang membabi-buta. Mereka justru sebenarnya bisa menjadi mitra strategis bagi negara jika diberi ruang untuk terlibat.
Problemnya adalah: negara kerap lebih suka mendengar pujian ketimbang kritik. Kecenderungan ini membuat literasi kritis diposisikan sebagai ancaman. Padahal, kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Ia bukan racun. Demokrasi tanpa kritik hanya akan melahirkan stagnasi.
Maka, ada baiknya kita melihat literasi sebagai investasi politik jangka panjang. Generasi muda yang membaca buku akan lebih siap menghadapi kompleksitas global. Mereka mampu membedakan fakta dan opini, propaganda dan informasi. Kualitas ini penting untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah arus deras informasi saat ini.
Jika negara terus-menerus mencurigai anak muda yang membaca buku, ia sebenarnya sedang merusak pondasi demokrasinya sendiri. Kecurigaan itu bisa membuat generasi muda merasa terasing dari negaranya. Mereka tidak lagi melihat negara sebagai ruang dialog, melainkan sebagai pengawas yang penuh syak wasangka. Konsekuensinya, kepercayaan mereka terhadap negara semakin terkikis.
Bisa Menyumbang Ide
Demokrasi memerlukan warga negara yang percaya diri dengan pikirannya. Anak muda yang membaca buku bisa menyumbang ide, solusi, dan inovasi. Semua itu hanya mungkin jika negara memberikan kepercayaan dan kebebasan literasi kepada mereka.
Dalam iklim demokratis, literasi seharusnya dilihat sebagai kekuatan, bukan ancaman. Membaca buku bukanlah tindakan kriminal. Membaca adalah hak asasi, sama pentingnya dengan kebebasan berbicara. Jika hak ini dipersempit, maka negara sedang mengingkari prinsip dasarnya sendiri. Demokrasi tanpa hak membaca ibarat tubuh tanpa oksigen.
Alih-alih selalu curiga, negara seharusnya memfasilitasi ruang baca yang luas dan terbuka. Perpustakaan publik, diskusi, dan forum literasi harus kian diperkuat. Ruang ini bisa menjadi arena dialog yang sehat antara negara dan warga. Dengan begitu, literasi benar-benar menjadi pilar demokrasi.
Demokrasi tidak bisa tumbuh di atas ketakutan. Demokrasi hanya bisa hidup di atas keberanian menerima kritik. Membaca buku adalah salah satu pintu menuju kritik itu. Karena itu, literasi harus diperlakukan sebagai bagian dari budaya politik yang sehat.
Negara yang percaya diri tidak takut pada warganya yang membaca buku. Justru ia bangga memiliki warga yang kritis dan berpengetahuan. Kepercayaan ini akan menciptakan hubungan politik yang sehat, yang berbasis dialog, bukan kecurigaan.
Pada akhirnya, membaca buku bukan sekadar aktivitas individu. Membaca adalah tindakan politik yang ikut menentukan masa depan bersama. Dari membaca buku, bisa lahir gagasan-gagasan untuk memperbaiki negeri. Dari gagasan-gagasan yang muncul, bisa lahir gerakan-gerakan sosial yang bisa membawa perubahan.
Maka, ketimbang terus-menerus curiga, negara seharusnya membuka diri. Anak muda yang membaca buku bukan musuh, melainkan harapan. Literasi adalah jembatan menuju demokrasi yang lebih matang. Tanpa itu, bangsa dan negara ini hanya akan berjalan di tempat lantaran miskin gagasan.***
--------------------------
DJOKO SUBINARTO
Kolumnis dan esais.